Krisis Logika
Oleh: Wie Ageng Puji Pinoto*
Ia tahu, tapi belum tentu mengerti, dan terbukti tidak mampu.
Sarjana merupakan salah satu kaum intelektual di kalangan masyarakat. Banyak masyarakat yang menganggap bahwa sarjana ibarat seorang pendekar. Pendekar, secara logis disebut sebagai pendekar apabila pada dirinya terdapat beberapa keadaan : Pendekar tahu dan mengerti semua jurus silat dan sanggup bermain silat.
Banyak orang digelari pendekar padahal ia hanya menguasai satu dua jurus silat. Ekspresi kependekarannya diwakilkan pada gaya perilakunya yang mencerminkan seakan-akan ia seorang jagoan. Tangan dan jarijarinya selalu digerak-gerakkan melontarkan kesan bahwa ia seorang pendekar. Namun orang banyak belum pernah manyaksikan ia sungguhsungguh mampu berkelahi.
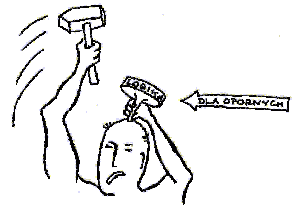 Gambar diambil dari http://azaleav.wordpress.com/2010/08/15/logika-oh-no/
Gambar diambil dari http://azaleav.wordpress.com/2010/08/15/logika-oh-no/
Ada juga orang yang disebut pendekar karena memiliki pengetahuan tentang semua jurus silat. Ia fasih berceramah tentang jurus dari sebelum masehi sampai jurus millennium. Namun kelemahannya cuma satu: begitu ia dipojokkan oleh keadaan di mana ia harus berkelahi, tahap pertama ia kebingungan akan mamakai jurus yang mana, tahap kedua ia lupa dan blank semua pengetahuannya mengenai jurus-jurus. Sehingga tahap ketiga ia tergeletak di-KO oleh lawannya.
Pendekar alias sarjana sejati, adalah orang yang sungguh-sungguh tahu tentang sesuatu hal yang ia pelajari. Yang benar-benar mengerti tentang apa yang diketahuinya, bisa, mampu, dan sanggup dalam mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata.
Universal Pendidikan Universitas adalah laboratorium untuk mempelajari segala sesuatu secara universal dan komprehensifholistik. Sedangkan fakultas adalah laboratorium untuk mempelajari sesuatu secara spesifik dan spesialistik.
Fakultas dari universitas adalah disiplin dimana pembelajaran spesialistik diorientasikan untuk menemukan keterkaitan dengan keilmuan yang universal dan komprehensif-holistik. Apakah kita semua ini akan menjadi sarjana Universitas ataukah sarjana Fakultas? Apakah kita semua akan menjadi sarjana keilmuan universal ataukah sarjana fakultatif? Apakah kita semua akan lulus telah mempelajari sesuatu secara spesialistik ataukah juga integral dengan universitas keilmuan makro?
Dalam kegiatan sehari-hari kita pergi ’kuliah’ ke kampus. Kata ’kuliah’ berasal dari kosakata kullu, yang dalam penggunaannya berarti ’semua’. Maka kuliah adalah proses pembelajaran yang bersifat universal meskipun kita berangkat secara fakultatif. Kalau dalam kenyataannya tidak ada garis sambung antara keilmuan fakultatif dan spectrum universal, maka kita tidak pernah berangkat kuliah. Yang kita lakukan adalah juz’iyah : belajar dalam skala fakultatifeksklusif, kemudian menjadi sarjana fakultas. Resikonya, kalau universitas hanya melahirkan sarjana fakultatif, lebih logis kalau nama lembaganya bukan Universitas, melainkan Paguyuban Fakultas-Fakultas.
Syarat lain seseorang disebut sarjana adalah bahwa ia memiliki segala sesuatu untuk menjadi problem solver, penyelesai masalah. Kalau seseorang membuat masalah, apalagi kehadirannya menjadi masalah baru lingkungannya, ia bukan sarjana. Tetapi apa gerangan bekal kita untuk menyelesaikan masalah? Kalau kuliah tidak berhubungan logis dengan pembelajaran universal, kalau universitas melahirkan sarjana fakultatif, kalau Tuhan adalah bagian dari kebudayaan manusia, kalau peribadatan agama tidak kauslitif-logis dengan perilaku sosial, kalau sistem sosial membunuh kemanusiaan, kalau demokrasi melarang Golput, maka pertama-tama yang kita temukan adalah Krisis Logika.
Kalau Reformasi adalah pemerataan korupsi, adalah pencurian kayu hutan meningkat 300% dibanding zaman sebelumnya, adalah release and discharge bagi raksasa-raksasa ’Sumanto’ pemakan massal daging rakyat, dimana maraknya Sumantoisme – dimana politik mengakali hak-hak rakyat, dimana kebudayaan memakan hidup-hidup martabat kemanusiaan rakyat, dimana Negara dan Pemerintahan adalah pengancam dan penipu atas rakyatnya, maka sebelum menyebut apapun saja dimensi dari multi-krisis bangsa kita, sebut dulu
Krisis Logika.
Indonesia yang krisis logika Penduduk Indonesia tidak mengerti benar siapa pemimpinnya. Penduduk Indonesia tidak mengerti benar siapa dirinya dalam berbagi konteks. Identifikasi goegrafis, birokratis dan administratif mungkin tahu. Tapi mereka tidak memiliki pengetahuan yang mendasar sama sekali mengenai identifikasi sosiologis mereka, alamat demokrasi mereka, serta berbagi sisi identifikasi yang mereka perlukan sebagai manusia, sebagai bagian dari kumpulan atau ummat, serta sebagai warga suatu negara.
Jangankan peta disinformasi dan diskomunikasi pada skala nasional dan tingkat komplikasi yang sedemikian tinggi, ilmu pengetahuan yang paling sederhana pun yang kita pelajari di kampus hanya sebatas pada beberapa buku dan catatan metodologi.
Pada hakekatnya hanya sebuah dhonn, sebuah persangkaan temporer, yang besok sore bisa digulingkan oleh persangkaan yang baru. Ilmu di sekolah memperoleh kehidupannya hanya karena diuji oleh ilmu di sekolah. Ilmu di buku seolaholah benar-benar ilmu karena pengujinya buku juga. Akan tetapi jika ilmu sekolah dan ilmu buku memang siap dibenturkan pada kenyataan kehidupan, kenapa tidak ada perbandingan sejajar antara meningkatnya jumlah sekolah dengan perbaikan sosial? Antara makin banyaknya Universitas dengan meningkatnya kualitas hidup bermasyarakat? Antara meningkatnya jumlah sarjana dengan grafik kemajuan bangsa?
Di dunia ilmu, sekolah, dan universitas belum benar-benar menemukan relevansi dan bukti dialektika dan integralitasnya dengan proses demokratisasi politik, dengan gradasi pencerdasan masyarakat, dengan menurunnya kebodohan, dengan peluang-peluangmenuju pemerintahan idaman. Bahkan sekedar arah logikanya terhadap kesempatan kerja di dunia industri dan pemerintahan pun semakin menurun.
Kini para penegak ilmu, penjunjung logika dan kebenaran, tidak punya banyak waktu lagi untuk melakukan konsolidasi makro. Indonesia sedang berada di puncak proses pembusukan, dan akan sungguh-sungguh memuncak kebusukan itu hanya pada beberapa tahun lagi. Kebanyakan pelaku kekuasaan bergiliran menjadi sampah. Apakah kita para sarjana, para pendekar mampu mengatasi masalah yang sedemikian ruwet ini? Ataukah kita juga akan menjadi sampah? Sebuah tanda tanya besar bagi kita semua.
*Penulis adalah Angota
tetap Anak Burung,
angota HIMAPTA
Mahasiswa Hama
Penyakit Tumbuhan
(HPT) 2002
canopy itu apa. ?
silahkan lihat di About CANOPY atau kunjungi kami di Facebook canopy